Oleh : Kunto Arief Wibowo
Sekitar tahun 70-an. Di belakang rumah Pak Yamin, banyak tumbuh rumpun bambu. Ukurannya besar-besar, sedikit berwarna kehitaman untuk yang sudah berumur tua. Sering disebut Bambu Betung (Dendrocalamus asper). Di bulan Ramadhan, beberapa bambu ini ditebang dan oleh anak-anak dijadikan bahan mainan yang disebut Meriam Bambu. Strukturnya yang keras membuatnya tahan untuk dijadikan meriam yang diledakkan dengan sumbu minyak.
Bagi Pak Yamin, bambu itu hampir tak berharga. Ia biarkan saja tumbuh liar, kadang dibersihkan jika daunnya sudah terlalu rimbun. Terkadang memang Pak Yamin mencoba menebang satu atau dua batang, kemudian dibawanya keliling kampung dengan sepeda ontel. Ada jugalah tetangga yang tertarik dan membeli sebatang, biasanya untuk dijadikan lantai rumah atau jadi tiang kandang ayam.
Begitulah yang terjadi, bambu itu terus tumbuh dan makin lebat setelah sekian tahun. Sampai kemudian Pak Yamin sudah tak ada lagi, rumpun Bambu Betung masih tumbuh rimbun.
Sampai kemudian di tahun 2000, seorang cucu Pak Yamin pulang ke kampung dan saat melihat kerimbunan bambu, muncullah ide barunya. Kebetulan ia bersekolah di Sekolah Teknologi Menengah (STM) atau SMK jika sekarang, sehingga ia terbiasa dalam mengolah sesuatu.
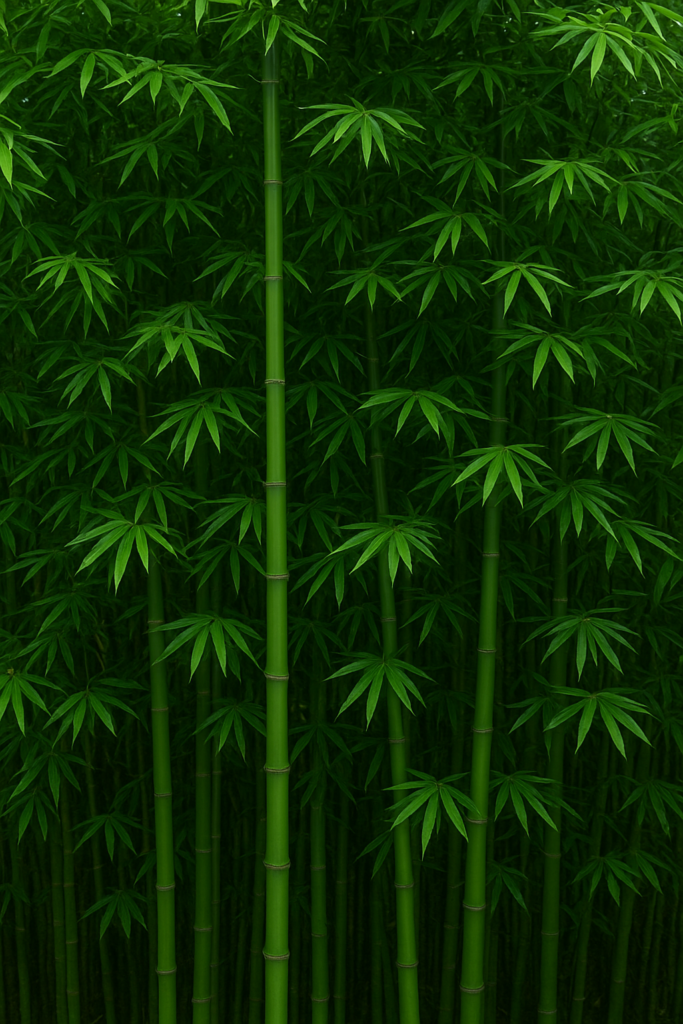
Segera saja, ditebangnya beberapa pohon bambu yang sudah tua, dipotong dengan ukuran tertentu, dibelah, dan dihaluskan. Disusun dan ditatanya bilah-bilah bambu sampai membentuk sebuah struktur tersendiri. Hasil karyanya kemudian menjadi sebuah kursi bambu yang halus, kuat dan menarik. Dipolesnya lagi menjadi lebih rapi, diberi cat dan diberi bahan pengkilap. Ia terus berkreasi, sampai akhirnya jadilah satu set meja bambu lengkap dengan kursinya.
Jika dulu Pak Yamin menjual sebatang bambu utuh seharga 20.000 rupiah, maka di tangan cucunya, 4 batang bambu yang sudah dikreasikan, dihargai senilai 2 juta rupiah. Perbedaan mendasar terlihat disini, Pak Yamin menjual bambu dalam bentuk bahan baku yang masih utuh, tapi cucunya menjual bambu dalam bentuk barang yang sudah punya nilai kemanfaatan tersendiri sekaligus bernilai seni.
Apakah yang dilakukan oleh cucu Pak Yamin tersebut? Itulah sebenarnya Hilirisasi.
Gagasan hilirisasi bukan hal baru di Indonesia. Aktifitas yang dilakukan para pengrajin, pengusaha-pengusaha kecil di kampung-kampung, sebetulnya sudah menunjukkan aspek olahan dari sebuah bahan baku. Tetapi memang hilirisasi model ini masih bersifat parsial dan belum terkelola dengan massif.
Di Norwegia, negara maju yang mengandalkan 80% perekonomiannya dari perdagangan, mengedepankan sekali aspek hilirisasi. Mulai dari minyak dan gas, sampai pada hasil produksi laut. Terutama sekali ekspor hasil kelautan seperti Ikan Salmon, Norwegia sangat serius mengelola ini. Samudra Atlantik sebagai sumber perikanan utama, betul-betul dimanfaatkan dan hasilnya dijual dalam bentuk olahan, bukan ikan mentah. Alhasil negara ini mampu mencatatkan diri sebagai salah satu negara dengan model downstream terbesar di dunia (Grudvag, et.all, 2022).
Begitupun yang terjadi di Australia, dimana mereka mampu dan terus konsisten memproduksi biji besi ketimbang biji besi mentah. Termasuk juga bagaimana Australia mendorong ekspor tekstil ketimbang bahan mentahnya. Ini juga sama dengan pengembangan sektor pertanian dan perikanan (OECWorld, 2025).
Kata kunci utama yang membuat hal ini bisa meningkat dan terus konsisten adalah tingginya kreatifitas, inovasi, serta dukungan penuh dari pemerintah. Jika dua unsur ini berpadu maka soal hilirisasi sebetulnya tinggal mengalir saja.
Konteks Indonesia, hilirisasi juga terkait unsur tersebut. Kita memiliki ragam SDA yang bisa diperoleh dengan mudah. Seperti contoh pak Yamin pada ilustrasi di awal, bambu bisa ada dimana saja, sangat mudah tumbuh dan berkembang bahkan tanpa harus dibudidayakan khusus. Perikanan juga demikian, tersebar dimana-mana.
Sampai saat ini, aspek tersebut belum maksimal ataupun merata dikembangkan. Padahal pada konteks sishankamrata, dari sudut pandang ketahanan nasional, SDA adalah komponen terpenting. Ketahanan Indonesia salah satunya bertumpu pada kekayaan SDA, dengan kata lain jika tidak mampu dimaksimalkan, yang terjadi adalah perebutan oleh negara lain ataupun sesama anak bangsa saling sikut.
Bagaimana keseriusan dalam aspek hilirisasi ini, khususnya kacamata pertahanan nasional melihatnya? Butuh memang sebuah kondisi khusus.
Pertama, hilirisasi memiliki komitmen untuk membangun kemandirian ekonomi seluruh rakyat dengan pendekatan ekonomi kerakyatan. Ini harus dijaga agar tidak sampai mengarah pada kelompok tertentu saja, khususnya pemodal besar. Hilirisasi berbasis ekonomi kerakyatan, bukan personal. Oleh sebab itu, dukungan dan pendampingan pada berbagai sektor agar mampu mandiri dan berdaya musti dilakukan.

Kedua, hilirisasi harus dalam kacamata transfer teknologi dan transfer ekonomi. Aspek pemberdayaan menjadi kunci disini. Kelompok masyarakat yang didorong untuk mampu mengolah ikan misalnya, harus menuju kemajuan dan kemandirian dalam mengolah ikan. Mereka harus diproyeksikan untuk menjadi pelaku-pelaku ekonomi sendiri, bukan lagi kelompok yang hanya bergantung pada satu atau sekelompok orang. Tentu butuh proses, oleh sebab itu hilirisasi tidak akan pernah selesai hanya satu atau dua tahun. Ia membutuhkan durasi keberlanjutan yang panjang.
Ketiga, hilirisasi sejatinya harus beranjak dari segala macam potensi kelokalan. Bukan merakit barang dari luar ke dalam negeri, tapi mengangkat segala potensi di dalam untuk kemudian mampu bertarung di dunia luar. Manfaatkan segala yang ada dan tersedia, tetapi bukan ekploitasi buta. Ini yang disebut sadar akan kekuatan dan paham dengan peluang. Seorang petani yang saban hari mengolah kebun palawijanya, harus mampu menciptakan produk-produk pertaniannya, namun dengan bahan baku apa yang ada disekitarnya. Jika ia mengolah hasil kebun tapi masih bergantung pada suplai bahan penunjang dari ekspor negara lain, itu bukan hilirisasi yang ideal. Rakyat akan tetap jadi lemah dan tergantung pada pihak lain.
Hilirisasi memiliki kata kunci, kuasa kelola dan kuasa manfaat. Masyarakat berkuasa untuk mengelola sesuka hati segala produknya dan berkuasa pula untuk menikmati manfaat tersebut. Pemerintah sudah menginisiasi ini semua, tinggal sekarang komponen yang lain untuk bergerak.






